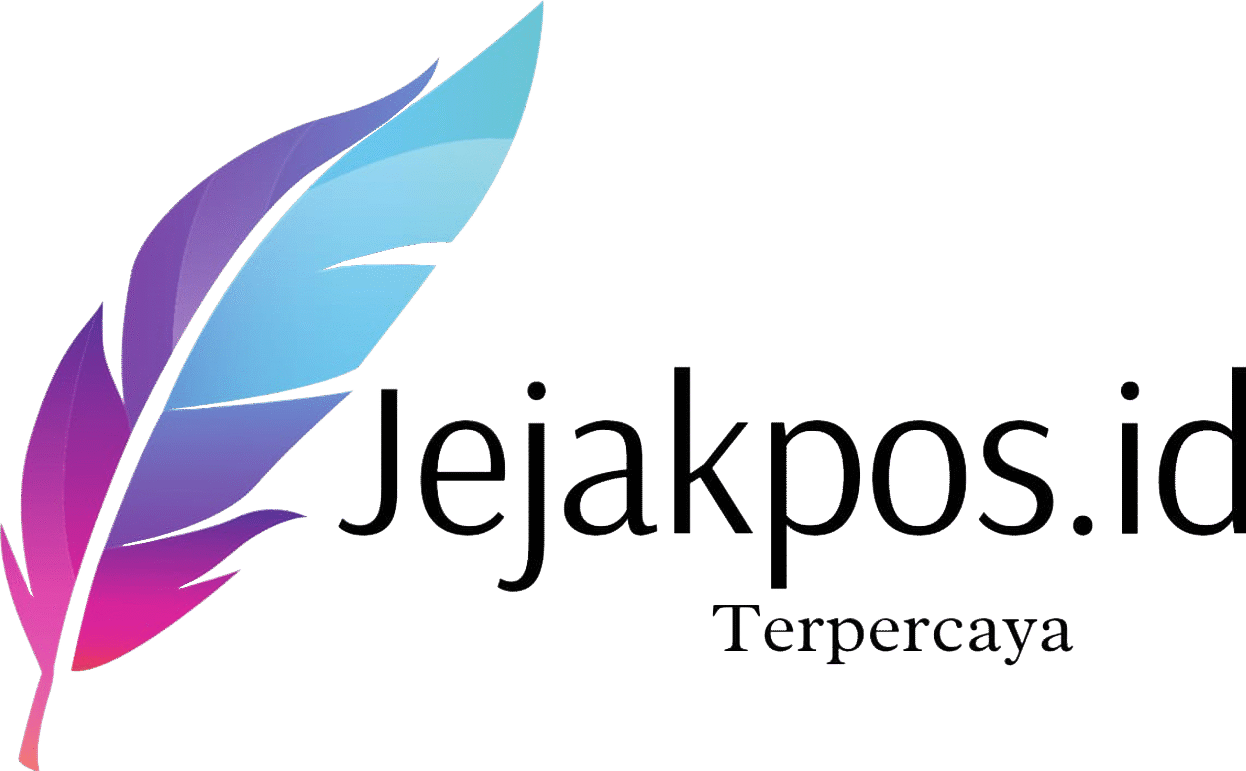Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Jakarta, Jejakpos.id – INDONESIA tampaknya masih terjebak dalam jerat klasik politik uang yang menggerogoti setiap lapisan proses elektoral. Berdasarkan survei exit poll yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 14 Februari 2024 ditemukan bahwa 46,9 persen responden pemilih menyatakan bahwa politik uang sesuatu yang wajar dan dapat diterima. Percaya atau tidak, survei ini adalah realitas proses elektoral yang teramati dan jamak terjadi di pemilu Indonesia kemarin. Politik uang dianggap kewajaran.
Tahun 2024 belum usai, proses elektoral selanjutnya yang akan dihadapi adalah Pilkada serentak. Proses Pilkada serentak pertama kali ini harusnya menjadi harapan untuk pembaruan budaya politik Indonesia. Politik yang mengedepankan kualitas dan substansi serta jauh dari ingar bingar transaksional. Namun harapan itu nampaknya masih terlalu jauh untuk diraih. Pilkada tetap berpotensi menjadi saksi dari episode tragis di mana modal finansial lebih berkuasa daripada suara rakyat. Alih-alih merayakan pesta demokrasi yang jujur dan adil, masyarakat mungkin justru kembali melihat parade koruptif yang berbalut janji manis dan tawa sinis. Baliho-baliho narsistik yang muncul untuk mengenalkan calon kepala daerah terlihat menawan, tetapi miskin gagasan. Masyarakat disuruh mengenal orangnya tanpa harus tahu isi kepalanya.
Namun memang hukum pasar politik sepertinya mengarah ke situ. Masyarakat dihukum dengan pilihan tanpa harus tahu alasannya. Maka pilihan yang muncul hanya didasarkan pada ikatan-ikatan emosional, tradisional, konservatif, dan kolot. Gagasan-gagasan politik bisa diganti dengan gugusan amplop. Politik hanya dimaknai sebatas alat tukar uang dengan kekuasaan. Dalam konteks ini, politik uang bukan sekadar praktik memalukan; ia adalah cerminan dari penyakit sistemik yang menggerogoti jantung demokrasi kita. Politik transaksional merupakan cerminan ketidakmampuan para elite politik untuk meraih dukungan rakyat dengan gagasan dan visi yang jelas sehingga memilih jalan pintas dengan membujuk pemilih melalui cara-cara yang tidak etis. Ini bukan hanya masalah moralitas individu, tetapi krisis struktural yang merongrong kualitas demokrasi dan budaya politik Indonesia.
Demokrasi tersandera oleh prilaku politik yang banal. Apakah demokrasi hanya sebatas permainan uang? Lalu apa yang bisa diharapkan dari proses demokrasi yang seperti itu? Demokrasi adalah tentang kedaulatan hakiki rakyat. Kedaulatan rakyat itu yang sedang disulap habis-habisan dengan pesona politik transaksional untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan pada ujungnya akan melahirkan dominasi. Dalam khazanah keilmuan sosial, Max Weber menjelaskan pelbagai macam dominasi yang muncul dari kekuasaan, yaitu dominasi karismatik, tradisional, dan legal rasional. Rumus politik yang muncul belakangan ini adalah antitesis dari teori Weber dengan memunculkan dominasi baru: dominasi modal. Kekuasaan hanya bisa dipegang dan diperoleh oleh mereka yang memiliki sumber daya dan dana politik terbesar, bukan oleh orang yang punya gagasan-gagasan besar. Calon kepala daerah yang jujur, punya visi, misi, gagasan, dan dedikasi mungkin tidak laku di pasar politik. Politik gagasan terus-terusan dihantam badai pragmatisme jangka pendek. Calon-calon yang hanya memunculkan gagasan akan tersingkir oleh orang yang punya “modal sosial” lebih besar dalam bentuk uang.
Ironis, bukan? Seharusnya demokrasi memberi kesempatan yang sama kepada semua orang, tetapi kenyataannya, setiap proses elektoral selalu menciptakan oligarki dan menambah panjang siklus koruptif. Efek domino dan siklus koruptif Robert Klitgaard salah seorang akademisi Amerika memperkenalkan model sederhana untuk memahami korupsi yang dikenal dengan rumus Klitgaard, yaitu: Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas. Dalam perspektif Klitgaard, korupsi tumbuh subur dalam kondisi di mana ada monopoli kekuasaan, kebebasan untuk membuat keputusan tanpa pengawasan, dan kurangnya akuntabilitas. Dalam konteks politik uang di Pilkada Indonesia, para calon kepala daerah yang memiliki sumber daya finansial besar dapat menciptakan monopoli kekuasaan melalui politik uang, mengurangi persaingan yang sehat dan adil. Setelah terpilih, para politisi ini memiliki diskresi luas dalam menggunakan anggaran dan membuat keputusan tanpa banyak pengawasan.
Lemahnya penegakan hukum dan institusi pengawasan yang tidak efektif menyebabkan tindakan koruptif menghegemoni setiap kebijakan dan pada akhirnya terbentuknya lingkungan koruptif di daerah. Hal tersebut ditambah lagi dengan keadaan masyarakat yang terus terlilit beban-beban ekonomi dan sosial sehari-hari. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit menjadi rentan terhadap politik uang. Mereka bergantung pada uang tunai dan bantuan langsung dari politisi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dimanfaatkan secara eksploitatif oleh politisi untuk mengamankan dukungan politik dengan memberi uang atau bantuan kepada pemilih. Terciptalah hubungan patronase ataupun klientalisme yang memperkuat ketergantungan masyarakat pada politisi (baca: uangnya politisi).
Praktik inilah yang berulang dari satu siklus pemilihan ke siklus pemilihan berikutnya, menciptakan efek domino dan lingkaran setan di mana korupsi dan ketidakadilan terus direproduksi. Struktur kekuasaan, ketergantungan ekonomi, dan kurangnya akuntabilitas menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik korupsi dan politik uang. Untuk memutus siklus ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik, peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih kuat, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada politisi. Antonio Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni, di mana kelas penguasa memanipulasi budaya dan ideologi untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Di Indonesia, hegemoni ini diwujudkan melalui politik uang, di mana para elite menggunakan sumber daya finansial mereka untuk memengaruhi hasil pemilihan dan memastikan dominasi mereka tetap terjaga. Ini menciptakan ilusi demokrasi, padahal yang terjadi adalah oligarki terselubung di mana kekuasaan hanya berotasi di kalangan elite tertentu. Setelah pilkada usai, biasanya muncul kesadaran susulan masyarakat bahwa hidup dan daerahnya tidak banyak berubah. Jalan-jalan tetap berlubang, pelayanan publik tetap buruk, dan korupsi merajalela. Kepala daerah yang dipilih hanya muncul insidental ataupun muncul karena adanya undangan ikatan jasa dari internal penyokongnya.

Untuk memutus siklus politik uang dan mengakhiri dominasi modal dalam Pilkada, diperlukan upaya bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat. Reformasi sistem politik, pendidikan politik yang intensif, dan penegakan hukum yang tidak pandang orang harus menjadi prioritas utama. Masyarakat juga harus diberdayakan secara ekonomi agar tidak lagi menjadi sasaran empuk. Tanpa upaya yang holistik dan berkelanjutan, demokrasi akan terus terperangkap dalam ilusi dan janji kosong. Pada akhirnya, politik yang muncul di pilkada nanti mungkin bukan hanya tentang kekuasaan dan uang saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tertawa di tengah kesulitan. Mungkin itulah seni politik Indonesia yang sesungguhnya: kemampuan untuk menemukan humor di setiap sudut tragedi politik.