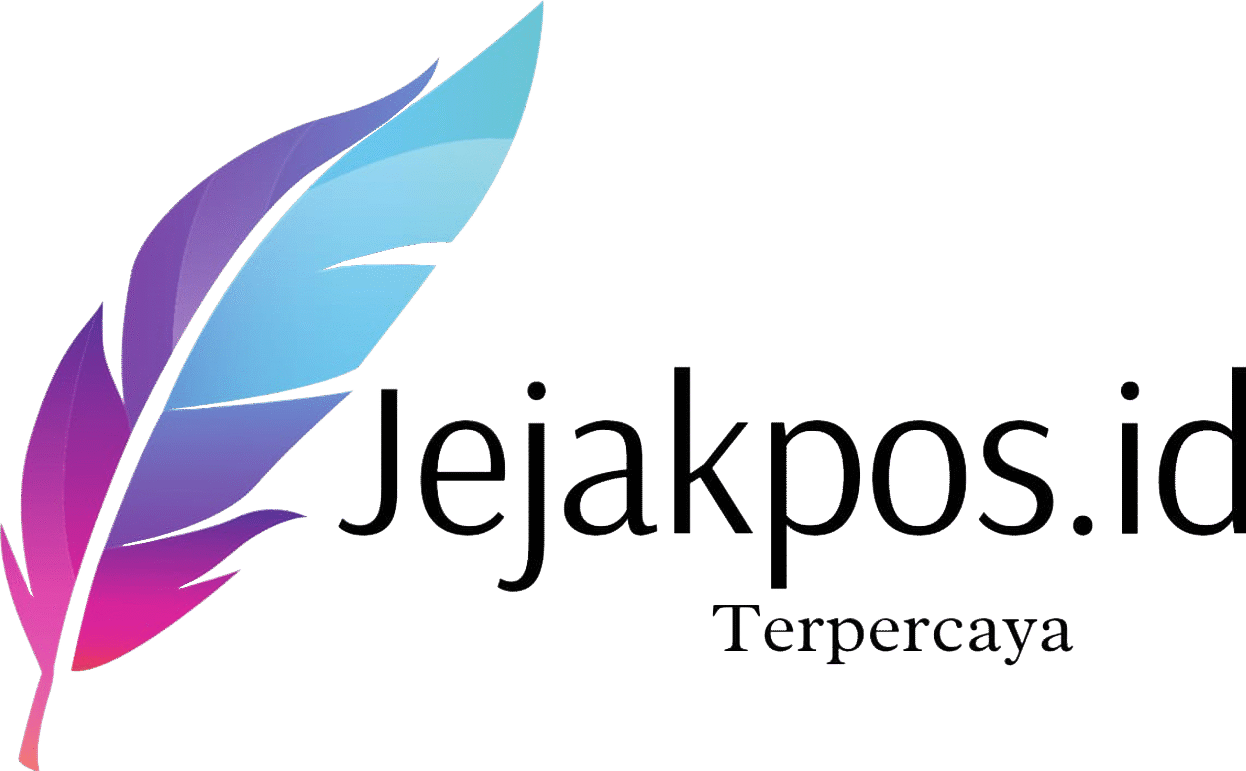Panggung Merdeka 100% : “Bekerja Lebih Sedikit, Hidup Lebih Baik, Dunia yang Adil untuk Semua”

JEJAKPOS.ID, JAKARTA – Di tengah perayaan 80 tahun kemerdekaan yang digembar-gemborkan pemerintah dengan klaim “delapan kemerdekaan,” realitas yang dihadapi mayoritas rakyat justru menunjukkan kontradiksi tajam. Alih-alih merdeka, rakyat masih terperangkap dalam siklus kerja eksploitatif, upah rendah, dan ketidakpastian ekonomi.
Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam diskusi yang digelar Panggung Merdeka 100% bertajuk “Bekerja Lebih Sedikit, Hidup Lebih Baik, Dunia yang Adil untuk Semua”. Diskusi ini menghadirkan beragam perspektif dari aktivis dan penggerak sosial, yaitu Ajeng Anggraini (Perempuan Mahardhika), Francesco Hugo (Suara Muda Kelas Pekerja), Echa Waode (Arus Pelangi), dan Guruh Riyanto (SINDIKASI).
Dalam paparannya, Ajeng Anggraini dari Perempuan Mahardhika menyoroti model ekonomi Indonesia yang menurutnya sangat eksploitatif. Ia menilai, negara hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
“Hidup kita direduksi jadi mesin kerja: tanpa istirahat, tanpa cuti, tanpa ruang bersosialisasi. Perempuan bahkan menanggung beban ganda, publik dan domestik,” ujar Ajeng. Ia menegaskan, sudah saatnya membalik logika pembangunan menjadi ‘kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja.’
Senada dengan Ajeng, Guruh Riyanto dari SINDIKASI mengkritik indikator ekonomi yang dominan, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), yang dianggapnya gagal mencerminkan kesejahteraan rakyat. Guruh mengusulkan pergeseran ukuran dari PDB ke kesejahteraan nyata pekerja.
“Dengan kemajuan teknologi dan AI, seharusnya waktu kerja bisa dikurangi, bukan malah ditambah,” jelas Guruh, seraya menambahkan bahwa pajak robot atau pajak AI bisa menjadi jalan untuk memperkuat jaminan sosial.
Diskusi juga menyoroti kerentanan yang dialami kelompok spesifik, khususnya anak muda dan komunitas LGBTIQ+. Francesco Hugo dari Suara Muda Kelas Pekerja menggambarkan bagaimana generasi muda kini hidup dalam jeratan kerja yang tidak stabil dan rawan eksploitasi.
“Kondisi kerja kita penuh eksploitasi halus: gaji stagnan, inflasi naik, dan ancaman layoff tiba-tiba,” ungkap Hugo. Ia menyerukan perlunya kerja yang transparan, demokratis, dan kolektif, serta mengusulkan koperasi sebagai jalan untuk membangun solidaritas melawan hegemoni kapitalis.

Sementara itu, Echa Waode dari Arus Pelangi menyoroti diskriminasi yang dihadapi pekerja LGBTIQ+ di tempat kerja. Ia menegaskan bahwa orientasi seksual atau identitas gender kerap dijadikan alasan untuk menghalangi akses terhadap pekerjaan layak.
“Padahal yang menentukan itu skill, bukan penampilan atau siapa yang kita cintai,” kata Echa, menambahkan bahwa negara tidak hanya gagal menyediakan pekerjaan layak, tetapi juga memungut pajak dari mereka sembari terus mendiskriminasi.
Fasilitator diskusi, Tyas Widuri dan Andini N dari Perempuan Mahardhika, menutup acara dengan menekankan pentingnya membangun imajinasi politik-ekonomi yang membebaskan.
“Kita terbiasa menerima eksploitasi seolah wajar, sehingga jarang membayangkan dunia lain yang adil. Padahal, keberanian berimajinasi itulah yang membuka jalan perubahan,” pungkas Tyas dan Andini.
Diskusi ini menegaskan bahwa kerja tidak boleh lagi menjadi sumber penindasan. Ruang percakapan kolektif, seperti yang difasilitasi dalam acara ini, adalah fondasi penting untuk membayangkan dan mengorganisir sebuah masyarakat di mana kerja tidak lagi menjadi penjara, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih layak bagi semua.
Tinggalkan Balasan
2 Komentar
-
Michael Crawford
Hi,
Are you still interested in our online transcription job openings? As mentioned on our website, applicants from your COUNTRY are encouraged to apply and full training is provided.
If you have a strong command of English listening and typing, access to the internet and are available for at least five hours per week, then this could be a great opportunity for you!
It’s quick and straightforward, and you’ll start earning $25-$35 per hour! Work directly with a small company and make a real difference to their business
All you have to do is click this link and complete your application: https://www.growthmarketingnow.info/audio .
I am excited to see your submission soon so we can get started on making money together!
Kind regards,
Michael CrawfordUNSUBSCRIBE: https://www.growthmarketingnow.info/unsubscribe/?d=jejakpos.id
Address: 1486 Confederate Drive
Cape Vincent, NY 13618 -
Clara Reeves
Hi jejakpos.id,
We invite you to participate in the paid survey, you are an expert within your industry, countless brands need your advice to improve their products and services. They will pay cash to you: https://www.increasetraffic.shop/survey.
Survey Junkie offers members many ways to interact with products and brands, paying members in cash in exchange for time spent doing certain activities. It’s free to join Survey Junkie, and you can choose which activities you will participate in to earn money.
This platform is a get-paid-to website that pays members to answer surveys, play games, and search the web. It’s owned by Prodege LLC, a market research company that specializes in customer engagement.
Survey Junkie has a Trustpilot rating of 4 out of 5 stars, which is respectable for a make-money website, and the Survey Junkie mobile app is available in both the Google Play store and Apple App Store, with 4.5- and 4.4-star ratings, respectively.
Now click here to make $50 a day: https://www.increasetraffic.shop/survey
Best regards,
Clara ReevesUNSUBSCRIBE: https://www.increasetraffic.shop/unsubscribe/?d=jejakpos.id
Address: 3713 Brentwood Drive
Austin, TX 78702