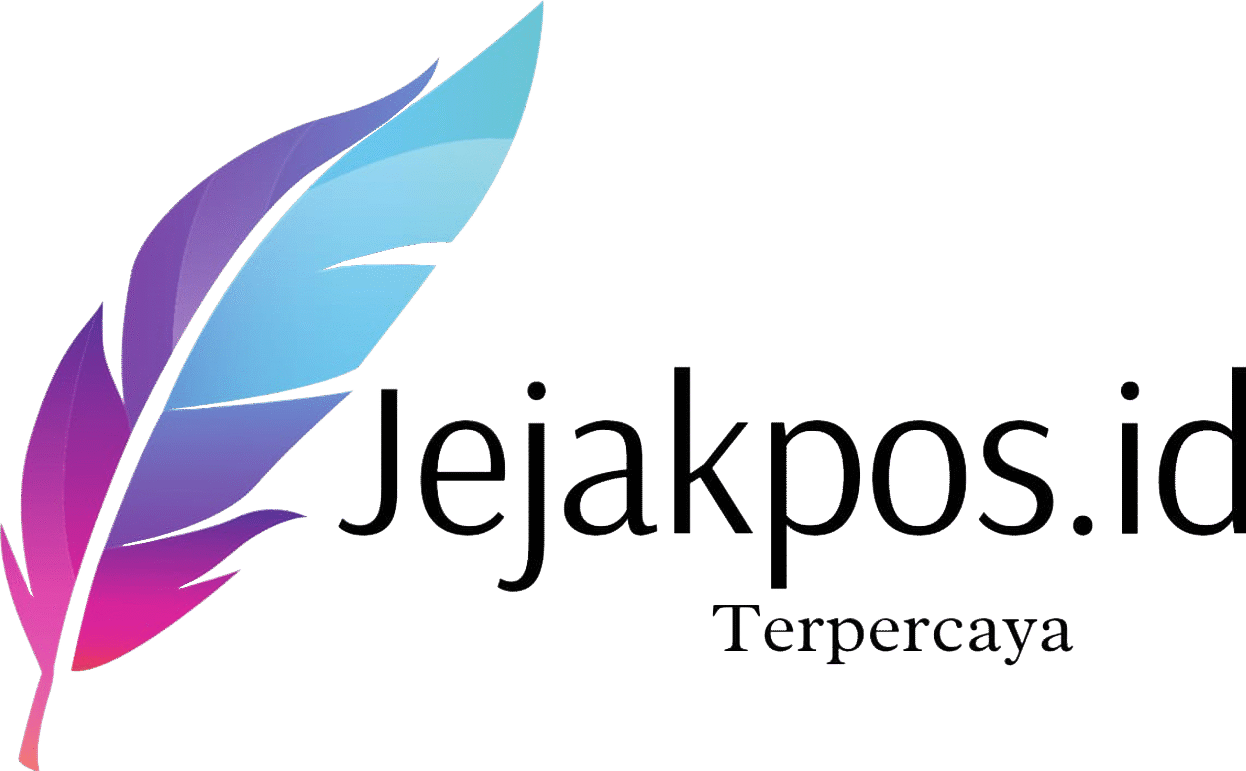Abolisi dan Amnesti di Tengah Demokrasi: Untuk Siapa Hukum Ditegakkan?

MALUKU, JEJAKPOS.ID – Ruang publik Indonesia kembali diwarnai perdebatan sengit menyusul langkah Presiden memberikan amnesti dan abolisi pada sejumlah kasus yang dinilai kontroversial. Keputusan ini memantik pertanyaan krusial di tengah desakan penegakan hukum yang tegas dan adil: untuk siapa hukum ditegakkan?
Di satu sisi, kewenangan pengampunan oleh negara dapat dibenarkan demi kepentingan nasional. Namun, di sisi lain, masyarakat menuntut jaminan bahwa hukum tidak diterapkan secara selektif atau berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Kebijakan yang seharusnya menjadi solusi hukum ini justru berpotensi memicu kembali luka lama, yakni ketidakpercayaan publik terhadap keadilan yang merata.
Langkah Presiden ini juga diambil pada momentum yang sensitif, menjelang tahun politik dan perubahan konstelasi kekuasaan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran banyak pihak bahwa kebijakan hukum sedang ditarik ke arah yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, di mana hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung hak warga negara, bukan instrumen politik.
Tinjauan Konstitusional dan Prinsip Kepastian Hukum
Dalam konteks hukum tata negara, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, namun dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Amnesti berfungsi menghapus akibat hukum dari tindak pidana tertentu, sementara abolisi menghentikan proses hukum terhadap perkara yang belum memperoleh putusan.
Namun, dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, kebijakan semacam ini memerlukan penilaian yang ketat. Terlebih, jika menyentuh kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama demi menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pengampunan atau penghentian perkara terhadap individu tertentu, terutama yang memiliki afiliasi dengan kekuasaan atau elite politik, seringkali menimbulkan persepsi ketimpangan dan keadilan yang tumpul.

“Keadilan tidak hanya diukur dari legalitas, tetapi juga dari rasa keadilan publik,” ungkap Rafik Dasuki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dalam narasinya. “Apabila kebijakan abolisi atau amnesti hanya menyentuh kalangan tertentu, sementara rakyat kecil tetap menjalani proses hukum secara penuh, maka keadilan menjadi tumpul dan selektif.”
Etika Pemerintahan dan Integritas Kepemimpinan Nasional
Dari ranah etika pemerintahan, keputusan seperti amnesti dan abolisi tidak hanya perlu benar secara hukum, tetapi juga harus benar secara moral. Dalam negara yang mengedepankan integritas institusi, keputusan hukum yang menyangkut kepentingan publik seharusnya tidak diambil secara tertutup atau transaksional.
Etika publik menuntut pemerintah untuk menjelaskan dasar, tujuan, dan dampak dari setiap kebijakan yang dapat memengaruhi sistem peradilan dan kepercayaan rakyat. “Ketika prosesnya dianggap tidak jujur atau bermotif politik, maka bukan hanya hukum yang diragukan, tetapi juga integritas kepemimpinan nasional,” tegas Dasuki.
Secara politis, kebijakan abolisi dan amnesti kerap digunakan sebagai alat rekonsiliasi nasional atau stabilisasi politik. Namun, jika digunakan untuk menyelamatkan kepentingan elite atau mengamankan jaringan kekuasaan, kebijakan ini dapat menjadi penyimpangan dari prinsip negara hukum yang demokratis.
Hukum sebagai Pelindung Demokrasi
Dalam konteks demokrasi, hukum seharusnya tidak berada di bawah tekanan politik, melainkan berdiri independen sebagai alat perlindungan hak warga negara. Ketika politik mengambil alih kontrol terhadap hukum, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penjamin keadilan dan transparansi.
Demokrasi sejatinya mengedepankan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi rakyat. Dalam sistem demokratis, pengambilan keputusan strategis seperti pemberian abolisi dan amnesti semestinya dilakukan secara terbuka, dapat diawasi, dan melibatkan mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Jika rakyat tidak diberi ruang untuk mengetahui atau menilai alasan di balik kebijakan tersebut, maka demokrasi kehilangan maknanya. “Demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu, tetapi mencakup hak rakyat untuk mengetahui, mengkritisi, dan menilai kebijakan negara, terutama yang menyangkut keadilan hukum,” pungkas Dasuki.