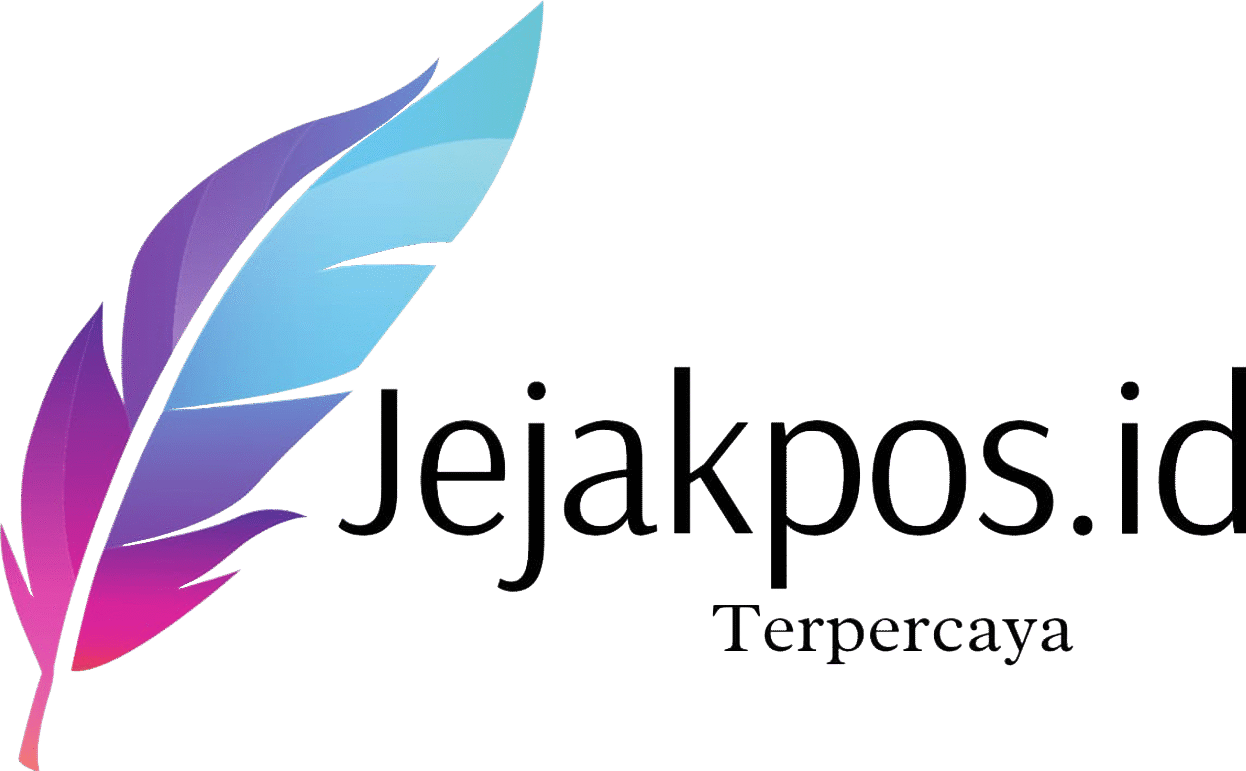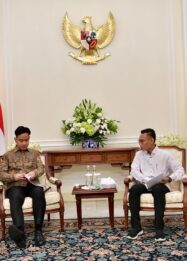FPMB Serukan Perlawanan Total Tolak Operasi Penyisiran

MALUKU, JEJAKPOS.ID – Awan mendung tampaknya belum beranjak dari kawasan tambang emas legendaris, Gunung Botak. Ketegangan yang sempat mereda kini kembali memanas, memicu keresahan yang menjalar cepat di kalangan ribuan penambang rakyat. Pemicunya adalah rencana operasi penyisiran yang akan dilakukan oleh aparat gabungan dan pihak terkait; sebuah langkah yang dinilai oleh banyak pihak sebagai lonceng kematian bagi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buru.
Di garda terdepan penolakan ini, Forum Pergerakan Mahasiswa Bupolo (FPMB) secara resmi mengambil sikap. Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan baru-baru ini, FPMB tidak hanya sekadar menolak, tetapi melayangkan peringatan keras bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal yang berbahaya.
Bagi ribuan masyarakat Buru, Gunung Botak bukan sekadar bukit yang mengandung logam mulia. Ia adalah “piring nasi”, urat nadi ekonomi, dan tumpuan harapan bagi para pemilik hak ulayat serta penambang kecil yang menggantungkan hidup keluarga mereka dari butiran emas di sana.
FPMB menilai, rencana penyisiran yang digulirkan tanpa didahului dialog terbuka adalah bentuk arogansi kebijakan. Langkah ini dianggap tidak memihak pada realitas sosial di lapangan, di mana ribuan nyawa bergantung pada aktivitas tambang rakyat tersebut.
Ketua Umum FPMB, Awin Hukul, dalam kajian mendalamnya menyoroti bahwa pendekatan represif melalui penyisiran bukanlah obat, melainkan racun bagi stabilitas daerah.
“Kami berdiri tegak untuk rakyat Buru. Penyisiran ini bukan solusi, melainkan ancaman nyata bagi mereka yang hidup dari tambang rakyat. FPMB akan terus melawan segala bentuk kebijakan yang mengabaikan keadilan sosial dan menindas kaum kecil,” tegas Awin dengan nada berapi-api.
Menurutnya, menyingkirkan penambang kecil tanpa memberikan skema perlindungan atau solusi alternatif sama saja dengan mematikan mata pencaharian rakyat secara paksa.
Suara perlawanan juga terdengar lantang dari Rafik Dasuki, mahasiswa asal Batabual yang turut menyuarakan kegelisahan masyarakat. Rafik menekankan bahwa perspektif pemerintah terhadap Gunung Botak harus diubah. Kawasan tersebut harus dilihat sebagai ruang sosial-ekonomi yang kompleks, bukan sekadar lokasi eksploitasi yang bisa ditutup buka semau pemangku kebijakan.

“Kami bukan menolak penataan, garis bawahi itu. Tetapi kami menolak cara-cara yang menyakiti rakyat,” ujar Rafik.
Ia menambahkan sebuah poin krusial dalam dinamika konflik sumber daya alam: “Jika pemerintah benar-benar berniat menata, maka libatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan menjadikan mereka korban yang tergusur dari tanahnya sendiri.”
Sikap FPMB tidak berhenti pada retorika di atas kertas. Organisasi ini telah menabuh genderang perlawanan yang lebih besar. Mereka mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang tidak hanya akan mengguncang Kabupaten Buru, tetapi juga akan digaungkan hingga ke pusat pemerintahan provinsi.
Gedung DPRD Provinsi Maluku dan Kantor Gubernur Maluku di Ambon telah dibidik menjadi titik sentral aksi mereka dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan politik (political pressure) agar suara lirih para penambang di pelosok Buru bisa didengar oleh para pengambil keputusan di tingkat provinsi.
“Jika suara masyarakat tidak didengar di Buru, maka kami akan bawa suara itu langsung ke Provinsi. Kami siap menggerakkan seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk memastikan hak-hak rakyat tidak diinjak-injak oleh kebijakan yang tidak berpihak,” seru salah satu Jenderal Lapangan FPMB, menyiratkan keseriusan gerakan ini.
Di ujung pernyataannya, FPMB mengirimkan sinyal darurat kepada seluruh elemen masyarakat Buru. Mereka mengajak para tokoh adat, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk merapatkan barisan. Isu Gunung Botak dinilai bukan lagi masalah sektoral, melainkan masalah martabat dan keberlangsungan hidup orang banyak.
FPMB memastikan bahwa gerakan penolakan penyisiran ini akan terus bergulir bagaikan bola salju, membesar dan terus menekan hingga pemerintah bersedia duduk bersama, membuka ruang dialog, dan menghadirkan solusi yang adil—bukan sekadar perintah pengosongan yang menyengsarakan.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah aspirasi ini akan didengar sebagai masukan konstruktif untuk penataan tambang yang humanis, ataukah akan diabaikan yang berpotensi memantik api konflik baru di Tanah Bupolo? Waktu yang akan menjawab.