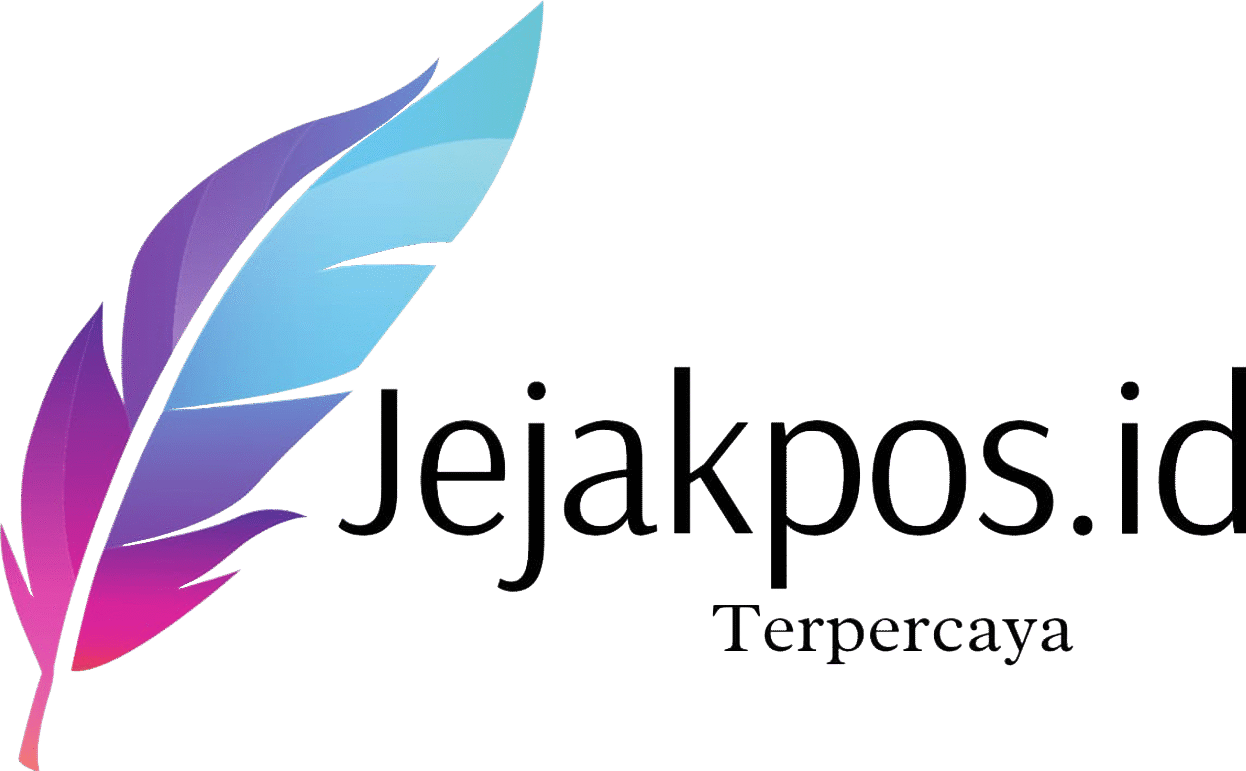Ironi Vonis 10 Bulan: Kasus Sertu Riza dan Darurat Reformasi TNI

JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Vonis 10 bulan penjara terhadap Sertu Riza Pahlivi, oknum TNI yang terbukti menyebabkan tewasnya siswa SMP berinisial MHS (15) akibat penganiayaan, adalah cermin buram dari ketidakadilan yang terus diproduksi oleh sistem peradilan militer di Indonesia.
Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 ini, alih-alih memberikan keadilan dan efek jera, justru memperkuat kritik lama masyarakat sipil: bahwa sistem peradilan militer adalah sarana utama untuk melanggengkan impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.
Kealpaan yang Berujung Kematian dan Vonis yang Mencederai Akal Sehat
Sertu Riza divonis bersalah atas tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Namun, bagaimana mungkin tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang remaja 15 tahun hanya diganjar hukuman kurang dari setahun?
Publik sulit menerima bahwa penganiayaan berat—bukan sekadar kecelakaan lalu lintas—hanya dianggap sebagai “kealpaan.” Vonis yang terlampau ringan ini tidak hanya mencederai rasa keadilan keluarga korban, tetapi juga mengirimkan pesan berbahaya kepada institusi TNI dan masyarakat: bahwa nyawa warga sipil yang diambil oleh oknum militer memiliki nilai yang murah di mata hukum militer.
Respons Pangdam: Pengakuan Keterbatasan Sistem
Reaksi dari Pangdam I/BB Mayjen Rio Firdianto yang mengaku tidak dapat mengomentari berat ringannya hukuman karena hal itu “sudah bukan tanggung jawab kami lagi,” secara tidak langsung mengakui adanya pemisahan tanggung jawab yang membuat pimpinan institusi militer terlepas dari akuntabilitas publik atas keputusan pengadilan.
Meskipun Pangdam menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai tingkat kesalahannya—dari disiplin hingga diserahkan ke Polisi Militer (PM) dan Oditur—fakta menunjukkan bahwa ujung dari proses tersebut (yaitu putusan di Pengadilan Militer) sering kali jauh dari harapan keadilan sipil. Proses tersebut berhenti di ranah militer dan terputus dari pengawasan dan standar keadilan umum.

Mandat Reformasi yang Terabaikan
Inilah saatnya kita kembali menagih janji Reformasi 1998 dan amanat Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 65 ayat (2) yang secara tegas menyatakan:
“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”
Kasus Sertu Riza adalah contoh nyata bahwa amanat tersebut, yang seharusnya memisahkan urusan militer dari urusan sipil, tidak berjalan di lapangan. Oknum TNI yang membunuh atau menganiaya sipil seharusnya diadili di Peradilan Umum, bukan Peradilan Militer.
Ketika kejahatan yang korbannya adalah sipil tetap diadili di peradilan militer, publik berhak meragukan independensi hakim dan objektivitas putusan, sebab hakim dan terdakwa berasal dari institusi yang sama, yang memiliki semangat esprit de corps yang kuat.
Mendesak Amandemen UU Peradilan Militer
Vonis 10 bulan untuk kasus pembunuhan adalah pukulan telak bagi supremasi sipil dan upaya reformasi sektor keamanan. Jalan satu-satunya untuk mengakhiri praktik impunitas ini adalah dengan mereformasi total payung hukumnya.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera mencabut atau merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Revisi ini harus memastikan bahwa:
1. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum (termasuk kekerasan, korupsi, dan kejahatan HAM) wajib diadili di peradilan umum.
2. Peradilan militer dibatasi hanya untuk mengadili tindak pidana murni militer, seperti desersi atau pembangkangan perintah.
Kasus MHS bukanlah kasus pertama, dan tanpa reformasi hukum yang radikal, bukan tidak mungkin ini juga bukan yang terakhir. Kepercayaan publik terhadap TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional dan berintegritas hanya bisa dipulihkan jika TNI menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan anggotanya di bawah standar akuntabilitas hukum yang sama dengan warga negara lainnya.