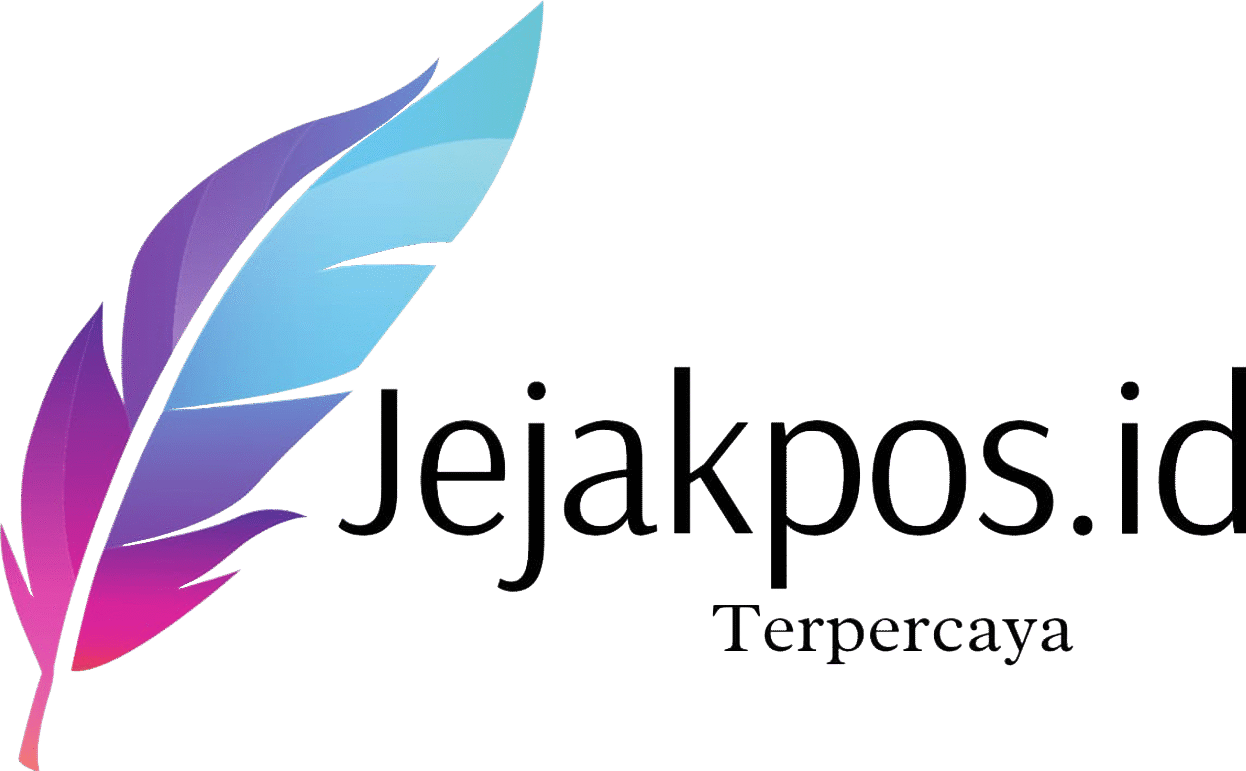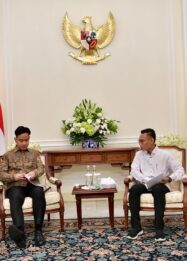Relasi Politik di Balik Pemberian Gelar Pahlawan

JAKARTA, JEJAKPOS.ID —Kebijakan negara belakangan ini yang memberikan status gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto telah memicu gelombang kontroversi di kalangan publik. Keputusan ini dinilai kontroversial mengingat Soeharto terbukti memiliki jejak kediktatoran yang kuat, serta indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang nyata, berdasarkan fakta sejarah dan memori kolektif rakyat.
Negara beralibi bahwa Soeharto adalah tonggak utama pertumbuhan ekonomi, menjadikannya “Bapak Pembangunan” saat Indonesia berusaha bangkit dari keterbelakangan pasca-kolonialisme. Namun, kontroversi semakin meruncing ketika gelar pahlawan juga diberikan kepada Marsinah, seorang pejuang buruh yang tewas dibunuh oleh kekuasaan. Hal ini menimbulkan implikasi adanya penyamarataan gelar pahlawan antara pelaku pelanggaran HAM dan korban pelanggaran HAM.
Situasi ini memantik diskursus dan mempertanyakan urgensi serta kelayakan pemberian gelar pahlawan.
Jejak Sejarah Gelar Pahlawan
Gelar pahlawan pertama kali diinisiasi pada masa Presiden Soekarno sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jasa serta kontribusi tokoh-tokoh yang berjuang melawan kolonialisme, mempertahankan kemerdekaan, dan meletakkan dasar-dasar kebangkitan negara di berbagai aspek.
Inisiasi ini dikonkretkan pertama kali pada tahun 1959 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 218 Tahun 1959 yang memberikan gelar pahlawan kepada Abdul Muis. Hingga tahun 2023, tercatat sudah ada 206 tokoh yang diberi gelar pahlawan. Secara umum, pemberian gelar ini dipandang mulia karena mengabadikan jasa para pejuang. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, proses ini seringkali disinyalir tidak terlepas dari kepentingan politik, indikasi pilih kasih, atau kedekatan emosional/politik.
Padahal, pemberian gelar pahlawan telah diatur secara substansial melalui mekanisme dan persyaratan yang ketat. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar pahlawan didefinisikan sebagai gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan, gugur demi membela bangsa dan negara, atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, serta menghasilkan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Syarat untuk memperoleh gelar, berpedoman pada Pasal 24 UU 20/2009, antara lain harus memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara minimal lima tahun.
Politisasi Gelar Pahlawan
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dinilai sulit diterima secara akal sehat. Rezim Orde Baru yang dipimpinnya diwarnai dengan penindasan, pembungkaman suara, pembatasan kebebasan sipil, dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya, seperti pembantaian massal 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Trisakti, hingga Penembakan Misterius (Petrus). Selain itu, terdapat pula upaya-upaya KKN yang masif di internal pemerintahan.

Secara hukum, negara telah mengakui terjadinya pelanggaran HAM masif di era Orde Baru melalui Keppres No. 17 Tahun 2022. Selain itu, TAP MPR X Tahun 1998 menyebutkan bahwa 32 tahun rezim Orde Baru terjadi penyelewengan kekuasaan. TAP MPR No XI tahun 1998 juga menetapkan rezim Soeharto sebagai sarang KKN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 140PK/Pdt/2015 memutuskan Yayasan SUPERSEMAR dan Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar denda kerugian.
Uraian hukum tersebut mengonfirmasi bahwa negara bergerak atas dasar inisiasi politik, bukan melalui kepastian hukum, refleksi nilai, atau pertimbangan fakta sejarah yang jelas. Kekuasaan justru berangkat dengan alibi rekonsiliasi demi menjaga ketenteraman negara dan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN). Negara dituding sengaja memberi doktrin pemahaman sejarah yang keliru agar masyarakat lupa akan fakta sejarah.
Jika Soeharto memperoleh legitimasi ketokohan melalui gelar pahlawan, dikhawatirkan segala upaya masyarakat sipil dan aktivis reformasi dalam melawan kediktatorannya dapat dianggap sebagai tindakan pembangkangan atau pengkhianatan negara. Kecurigaan politisasi semakin menguat dengan penyejajaran tokoh seperti Marsinah, korban kejahatan negara, dengan Soeharto, seolah-olah negara bersikap adil dalam menghargai jasa pahlawan.
Uraian ini memberikan kepastian bahwa pemberian gelar pahlawan tidak terlepas dari kepentingan politik, didasarkan pada relasi kuasa dan hubungan balas budi, alih-alih kesadaran moral atas jasa para pahlawan.