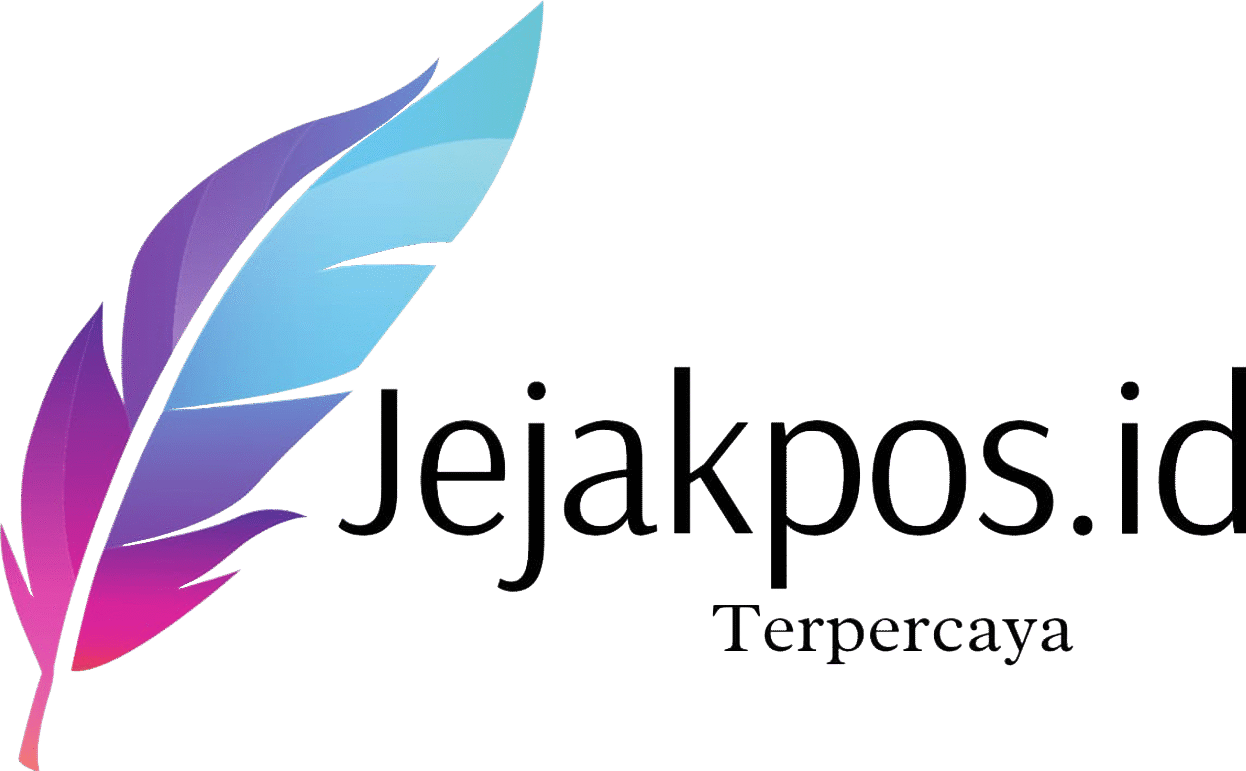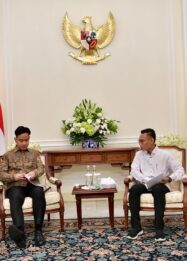Saat Hak Pilih Rakyat ‘Dikebiri’ di Ruang Rapat DPRD

JAKARTA, JEJAKPOS.ID – Awan mendung tengah menggelayuti langit demokrasi Indonesia. Di tengah riuh rendah perpolitikan nasional, sebuah wacana kontroversial kembali menyeruak dari Senayan, mengancam untuk merenggut salah satu hak paling fundamental yang dimiliki rakyat: hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara langsung.
DPR-RI kini tengah serius menggodok usulan perubahan sistem pemilihan bupati. Jika usulan ini lolos, kotak suara rakyat akan digantikan oleh ketukan palu segelintir elite di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebuah langkah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai “langkah mundur” yang nyata bagi perjalanan demokrasi pasca-reformasi.
Gelombang wacana ini bukanlah riak kecil yang tiba-tiba muncul. Ia adalah ombak yang terencana, didorong oleh kekuatan-kekuatan politik raksasa.
Wacana ini menemukan momentumnya pada pertengahan tahun 2025. Tepatnya pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, melempar bola panas tersebut. Alasannya klise namun “seksi” di telinga para politisi: menekan ongkos politik yang gila-gilaan dan meminimalisir praktik politik uang yang kian brutal dalam Pilkada langsung.
Namun, bola panas itu berubah menjadi bola salju raksasa beberapa bulan kemudian. Pada peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, 5 Desember 2025, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka dan lantang mengusulkan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Gayung pun bersambut. Presiden Prabowo memberikan sinyal positif atas gagasan tersebut. Lampu hijau dari eksekutif dan legislatif ini seolah menjadi penanda bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang baru akan menjadi pintu masuk bagi kembalinya sistem demokrasi perwakilan ala Orde Baru.
DPR-RI berdiri di atas argumen efisiensi. Narasi yang dibangun cukup rapi: Pilkada langsung boros, memicu konflik horizontal antar-warga, dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten karena hanya bermodalkan popularitas. Dengan pemilihan oleh DPRD, mereka mengklaim akan terjadi seleksi yang lebih ketat, objektif, dan menghasilkan bupati yang berintegritas serta memiliki kemampuan teknokratis yang mumpuni.
Namun, benarkah demikian? Atau ini hanyalah eufemisme untuk mempermudah pembagian kekuasaan?

Kritik tajam datang menghujam argumen tersebut. Publik menilai alasan “mahalnya ongkos politik” hanyalah kedok. Mengembalikan pemilihan ke DPRD justru dikhawatirkan akan memindahkan “loket” politik uang—dari serangan fajar ke rakyat, menjadi transaksi “borongan” di ruang-ruang tertutup gedung dewan. Politik transaksional diprediksi akan semakin subur, namun kali ini hanya dinikmati oleh segelintir anggota dewan.
Jika wacana ini menjadi nyata, dampaknya akan terasa jauh ke depan. Kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang sudah rendah, bisa mencapai titik nadir. Demokrasi akan berubah menjadi oligarki di mana keputusan-keputusan strategis daerah hanya berputar di lingkaran setan elite politik.
Penutup analisis Farhan memberikan sebuah peringatan keras sekaligus solusi: “Untuk mencegah kemunduran demokrasi, sistem pemilihan harus lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.”
Rakyat kini dihadapkan pada persimpangan jalan. Apakah Indonesia akan terus melaju sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang menghargai suara setiap warganya? Ataukah kita akan membiarkan hak rakyat “dikebiri” atas nama efisiensi, dan membiarkan demokrasi mati perlahan di tangan wakil rakyatnya sendiri?
Waktu yang akan menjawab, namun lonceng peringatan telah berbunyi keras.