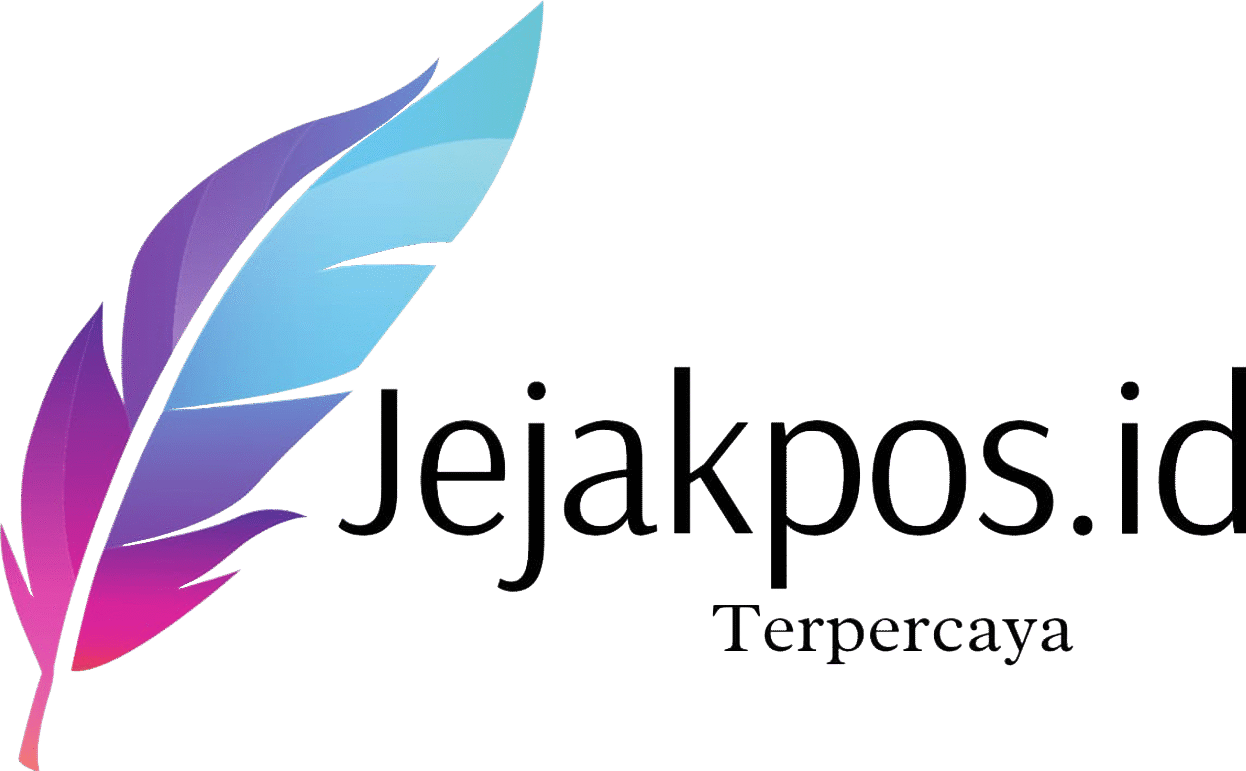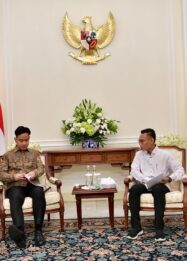Sumatera Terjebak di Kegelapan Pasca-Bencana, Akses Logistik Terputus Total.

SUMATERA, JEJAKPOS.ID – Lebih dari sepekan berlalu sejak bencana maha dahsyat melanda Pulau Sumatera, namun jeritan kepedihan dan ketidakpastian masih menggantung di udara. Bagi ribuan korban banjir bandang dan tanah longsor yang kini hanya bisa menggali harapan di antara puing, waktu seolah berhenti di tanggal 26 November 2025—hari ketika segalanya tersapu dalam sekejap.
Di awal musibah, warga masih memegang erat harapan agar kerabat yang hilang segera ditemukan. Namun, seiring berjalannya waktu dan lambatnya bantuan yang menjangkau lokasi-lokasi terisolasi, harapan itu perlahan luntur, berganti menjadi sebuah kepasrahan yang memilukan. Nama-nama yang dicari di sela-sela timbunan lumpur kini hanya tercatat dalam daftar panjang orang hilang.
Bencana ini datang dengan kecepatan yang mengerikan, jauh melampaui kemampuan mitigasi maupun respons bantuan darurat. Hujan yang turun berhari-hari tidak lagi sekadar air, melainkan berubah menjadi arus pekat berisi lumpur, batu, dan yang paling mematikan: kayu gelondongan. Pemandangan ini seolah menjadi simbol kemarahan alam—sebuah konsekuensi pahit dari hutan-hutan yang telah digunduli secara masif di masa lalu.
Di pulau yang kaya akan alamnya, kini ribuan keluarga ditinggalkan dengan luka yang dalam, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan yang tak ternilai harganya: anggota keluarga.
Data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu, 6 Desember 2025, menunjukkan skala tragedi yang terus membesar. Angka korban jiwa telah mencapai 914 jiwa meninggal, sementara 389 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Ironisnya, angka ini hanyalah puncak gunung es.
Pihak berwenang meyakini bahwa jumlah korban pasti akan bertambah signifikan. Sebab, masih banyak wilayah—terutama di pedalaman—yang sama sekali belum tersentuh oleh tim penyelamat. Infrastruktur yang hancur total membuat akses menjadi mimpi buruk.
Laporan dari lapangan menggambarkan kondisi isolasi yang kritis. Daerah-daerah vital seperti Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan di Sumatera Utara, hingga Aceh Tamiang di ujung utara pulau, kini benar-benar terputus dari dunia luar. Jalan-jalan utama hancur lebur diterjang banjir, tiang-tiang listrik tumbang memadamkan penerangan, dan jaringan komunikasi terputus total.
Kondisi ini menciptakan kegelapan informasi yang ganda. Selain sulitnya tim evakuasi menjangkau korban, warga di satu desa bahkan tidak bisa mengetahui nasib kerabat mereka di desa tetangga, memicu kepanikan dan kekhawatiran yang mendalam.

Di tengah situasi yang mencekam ini, suara-suara warga terdengar penuh kepedihan. Mereka yang selamat terpaksa harus bertahan sendirian, mengandalkan sisa makanan dan kemampuan bertahan seadanya, menanti pertolongan negara yang terasa begitu jauh dan lambat tiba.
Salah satu kisah pilu datang dari Aramiko, seorang warga di Kampung Pantan Nangka, Aceh Tengah. Ia hampir kehilangan akal dan harapan setelah menunggu lebih dari seminggu.
“Kami sudah hitungan hari bertahan di sini. Makanan menipis, anak-anak mulai sakit. Kami dengar bantuan sudah sampai di kota, tapi ke sini tak kunjung tiba,” lirih Aramiko.
Isolasi geografis wilayahnya, diperparah dengan rusaknya jembatan dan jalan penghubung, telah menjadikan Pantan Nangka sebuah ‘pulau’ yang terpisah dari rantai logistik bantuan. Kisah Aramiko adalah representasi ribuan warga lainnya yang kini hanya bisa menatap langit, berharap hari esok membawa secercah pertolongan sebelum kepasrahan menjemput mereka sepenuhnya.